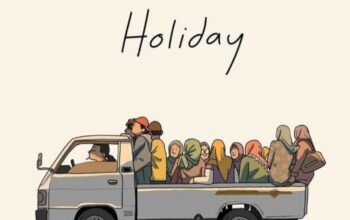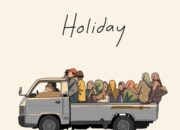Latar belakang ini menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam berupa lahan di lereng-lereng Gunung Hyang Argapura menjadi pusat perhatian Belanda dengan praktik membuka perkebunan konsentris, terutama lereng selatan dan timur yang mungkin merupakan satu kesatuan peradaban yang terbagi pada beberapa titik atau desa sebelum kedatangan pengusaha kebun yang diorganisir oleh pemerintah Kolonial.
Saya lebih cenderung merujuk pada istilah “perkebunan konsentris” yang tidak umum digunakan dalam literatur perkebunan atau agrikultur. Namun, jika menguraikan istilah tersebut, “konsentris” berarti sesuatu yang memiliki pusat yang sama atau berpusat pada satu titik beserta apa yang ditanam adalah lebih mono kultur. Dalam konteks perkebunan, ini bisa merujuk pada tata letak atau desain perkebunan yang terorganisir dalam pola melingkar atau berpusat pada satu titik utama, seperti pusat pengolahan atau fasilitas utama lainnya, termasuk penyerapan tenaga kerjanya.
Perubahan Budaya dan Kesenian di Dusun Durjo Karang Pring
Peradaban di lereng Gunung Hyang Argapura mengalami banyak perubahan selama tiga abad, setelah era klasik akhir atau runtuhnya Majapahit dan kemudian diteruskan oleh Demak dan Mataram, hingga pembukaan perkebunan konsentrasi Belanda pada 1900-an.
Perubahan ini membentuk model budaya dan kesenian yang bereaksi dan paling tidak sangat reaktif terhadap penguasaan lahan secara tiba-tiba oleh pengusaha asing yang membuka lahan kebun di Jember.
Ini sangat kentara ketika dalam proses telusur Sandur Tanean menyampaikan, yang pada garis besarnya adalah Sandur Tanean bukan mewakili entitas perkebunan dan warga yang bekerja di perkebunan memang secara lisan dan praktek tidak menonton kesenian Sandur Tanean dan bukan bagian dari pelaku Sandur Tanean. Apakah ini muncul secara tiba-tiba? Saya kira tidak mungkin, karena tidak mungkin ada panas tanpa api.
Masa kolonial dan munculnya Agrarische Wet atau undang-undang agraria yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1870, dan mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan tanah di Hindia Belanda, ternyata secara langsung memotong sumber penghidupan kelompok warga, terutama di lereng selatan Gunung Hyang Argapura, yang telah dilakukan turun menurun.
Kemudian juga munculnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960, untuk menggantikan Agrarische Wet. UUPA 1960 ini bertujuan untuk mengatur kembali kepemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia. Secara sederhana bahwa UUPA 1960 nanti akan menjadi bahan bakar meletusnya peristiwa 1965-1966, yang dikenal dengan G30SPKI saat ini.
Ada contoh menarik dari Dusun Durjo Karangpring, sebagaimana yang diungkapkan Pak Kasim Ketua LMDH Karangpring, dalam satu sesi diskusi dalam Pesta Sastra Hyang Argapura 2024, bagaimana petani yang tidak memiliki lahan kemudian mengolah lahan perhutani sejak tahun 1978.
Ini adalah cerminan konflik SDA berupa lahan olahan yang memiliki akar lama sejak jaman kolonial.
Pengaruh Perubahan Iklim serta Hubungannya dengan Pengetahuan Lokal
Perubahan iklim juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi peradaban ini. Tercatat bahwa pengalaman pertama manusia pada perubahan iklim telah terjadi masa glasial atau mencairnya es pada 250 ribu sampai dengan 10 ribu tahun yang lalu, kemudian singkatnya permukaan air laut naik dan menenggelamkan paparan sundaland dan memisahkan Pulau Madura dan Pulau Jawa menjadi selat Madura.